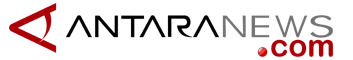Jakarta (ANTARA News) - Karakteristik mental seseorang yang toleran bisa dikondisikan, dikembangkan, dan dimantapkan lewat membaca seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya segala macam kisah kehidupan manusia dan sejarah pemikirannya.
Tentu membaca adalah salah satu jalan untuk menjadi toleran. Memperluas jaringan pertemanan dengan segala macam latar belakang individu juga jalan ampuh untuk menjadi sosok yang toleran.
Isu toleransi dan antonimnya, yakni intoleransi, belakangan ini sering menjadi wacana publik. Apalagi momentum menjelang Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 secara langsung atau tak langsung menjadi bingkai politik terjadinya kasus-kasus intoleransi.
Harus diakui bahwa beberapa politikus memainkan isu-isu keimanan untuk kepentingan ideologis mereka dengan menyeret-nyeret perkara privat keyakinan keagamaan ke ruang publik.
Sayangnya, manuver politikus yang kurang ideal bagi pengembangan demokrasi itu kadang mendapat dukungan dan ruang berekspresi dari lembaga penyiaran. Salah satu contoh: sebuah acara tayang bincang di sebuah televisi swasta menyelenggarakan dialog yang bertema adu keislaman para kandidat presiden.
Tema semacam ini jelas sangat personal dan kurang berfaedah bagi pengembangan demokrasi. Di samping itu, bagaimana mengukur kualitas keberagamaan seseorang yang jelas-jelas hanya Dia yang Maha Kuasa yang berhak menghakimi kualitas iman ciptaan-Nya.
Pertarungan politik selayaknya dilepaskan dari perkara keimanan. Namun, sebagian politikus melihat bahwa tak sedikit warga negara, apalagi mereka yang menjadi bagian mayoritas akar rumput belum menyadari konsep sekularisme dalam politik.
Seruan kepada kaum awam bahwa memilih capres anu akan memperoleh ganjaran surgawi masih terdengar dengan argumen teologis yang sumir, argumen yang mengada-ada.
Yang sulit diterima nalar adalah bahwa para kandidat presiden pada Pilpres 2019 adalah sama-sama pemeluk Islam. Jika para kandidat itu berbeda agama, memainkan isu keimanan boleh jadi masuk akal sekalipun fatal akibatnya.
Namun, karena kedua capres itu sama dalam pilihan iman, dicarilah sisi-sisi yang menguntungkan secara politis dengan mengadu kualitas keislaman para kandidat.
Tentu Komisi Pemilihan Umum tak gegabah mengikuti wacana sensasional yang digulirkan pihak televisi swasta yang targetnya untuk meraih penonton sebanyak mungkin dengan mendiskusikan tema-tema yang memancing reaksi keras baik dari kaum intoleran maupun kelompok toleran itu.
Alih-alih mendialogkan perkara kualitas keislaman kandidat presiden, akan lebih bermanfaat jika televisi swasta itu mengangkat tema bagaimana mencegah lahirnya pribadi-pribadi intoleran bagi pengembangan demokrasi di Tanah Air.
Tokoh-tokoh pembicara yang bisa ditampilkan antara lain kaum moderat maupun militan intoleran baik dari kalangan rohaniman Muslim, Kristiani, Buddhis atau pengikut kepercayaan lain.
Intoleransi sebagai masalah perpolitikan bisa muncul di lingkungan agama apa pun. Dengan kata lain, setiap sistem keimanan dihuni oleh penganut-penganut garis keras, yang tak memberi ruang toleransi bagi kelompok di luar sistem keimanan yang mereka anut.
Intoleransi sesungguhnya merupakan paradoks dalam setiap sistem kepercayaan. Setiap agama mengajarkan kepada pemeluknya bahwa hanya Sang Khalik yang berhak memvonis siapa yang benar dan yang tak benar.
Namun, dalam laku keseharian, apalagi dilandasi oleh seruan politikus yang sedang berkampanye untuk kepentingan politik mereka, ajaran teologis itu terkesampingkan.
Tampaknya, ada salah satu jalan yang bisa digunakan untuk membentengi diri dari kemungkinan terjeblos ke lembah intoleransi itu, yakni membaca sebayak mungkin kisah kehidupan manusia baik dalam bentuk biografi orang terkemuka maupun fiksi sejarah, terutama yang menyangkut konflik keimanan yang berdarah-darah.
Dari biografi atau otobiografi tokoh semacam Mahatma Gandhi, pembaca bisa menemukan hikmah dari eksperimen-eksperimen Gandhi tentang kebenaran. Dilengkapi dengan menyaksikan film kolosal tentang perintis kemerdekaan India itu, seseorang akan menghayati betapa berharganya memiliki sikap mental toleran. Puncak intoleransi hanya melahirkan penderitaan umat manusia.
Pembaca juga bisa mengambil hikmah tentang betapa pentingnya memiliki sikap toleransi lewat buku Kebenaran yang Hilang karya Farag Fouda, intelektuali Mesir, yang berkisah tentang praktik politik dan kekuasaan dalam sejarah kaum Muslim.
Dari buku fiksi, salah satu yang bisa memberikan pencerahan terhadap pembaca adalah novel klasik karya Umberto Eco yang berjudul The Name of Rose. Dari penyajian karya ini, pembaca disuguhi bagaimana sikap-sikap intoleran bisa memunculkan berbagai bentuk kebengisan manusia, yang tak disadari sang pelaku.
Untuk memantapkan pandangan personal tentang betapa pentingnya bersikap toleran kepada orang lain, buku yang layak dicerna adalah teks-teks karya pemikir eksistensialisme semacam Friedrich Nietzsche, Soren Kierkegaard, Jean Paul Sartre dan Dostoyevski.
Memperluas spektrum bacaan dengan menjelajah berbagai aliran filsafat yang paling ekstrem akan menumbuhkan sikap-sikap lapang dada yang pada akhirnya menimbulkan kesadaran personal tentang beragamnya pemikiran manusiawi.
Semakin banyak warga negara yang memiliki penghayatan dan kesadaran tentang keberagaman pemikiran kemanusiaan akan semakin positif bagi pengembangan demokrasi.
Dari keluasan bacaan yang merambah ke berbagai pemikiran hingga yang paling ekstrem inilah, seseorang akan menyadari betapa kompleksnya makna kebenaran.
Ketika seseorang tak dengan mudah mengklaim menemukan dan mengetahui kebenaran, seiring dengan itu tak mudah gegabah pula dia mendaku dirinya sebagai pihak yang paling benar. Di sinilah esensi sikap toleran seorang individu.
Baca juga: Amnesti Internasional: Etnis Uighur diperlakukan diskriminatif
Baca juga: Ratusan pakar kutuk China atas pembangunan pusat penahanan di Xinjiang
Baca juga: China tahan sejuta warga Uighur di fasilitas rahasia
Tentu membaca adalah salah satu jalan untuk menjadi toleran. Memperluas jaringan pertemanan dengan segala macam latar belakang individu juga jalan ampuh untuk menjadi sosok yang toleran.
Isu toleransi dan antonimnya, yakni intoleransi, belakangan ini sering menjadi wacana publik. Apalagi momentum menjelang Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 secara langsung atau tak langsung menjadi bingkai politik terjadinya kasus-kasus intoleransi.
Harus diakui bahwa beberapa politikus memainkan isu-isu keimanan untuk kepentingan ideologis mereka dengan menyeret-nyeret perkara privat keyakinan keagamaan ke ruang publik.
Sayangnya, manuver politikus yang kurang ideal bagi pengembangan demokrasi itu kadang mendapat dukungan dan ruang berekspresi dari lembaga penyiaran. Salah satu contoh: sebuah acara tayang bincang di sebuah televisi swasta menyelenggarakan dialog yang bertema adu keislaman para kandidat presiden.
Tema semacam ini jelas sangat personal dan kurang berfaedah bagi pengembangan demokrasi. Di samping itu, bagaimana mengukur kualitas keberagamaan seseorang yang jelas-jelas hanya Dia yang Maha Kuasa yang berhak menghakimi kualitas iman ciptaan-Nya.
Pertarungan politik selayaknya dilepaskan dari perkara keimanan. Namun, sebagian politikus melihat bahwa tak sedikit warga negara, apalagi mereka yang menjadi bagian mayoritas akar rumput belum menyadari konsep sekularisme dalam politik.
Seruan kepada kaum awam bahwa memilih capres anu akan memperoleh ganjaran surgawi masih terdengar dengan argumen teologis yang sumir, argumen yang mengada-ada.
Yang sulit diterima nalar adalah bahwa para kandidat presiden pada Pilpres 2019 adalah sama-sama pemeluk Islam. Jika para kandidat itu berbeda agama, memainkan isu keimanan boleh jadi masuk akal sekalipun fatal akibatnya.
Namun, karena kedua capres itu sama dalam pilihan iman, dicarilah sisi-sisi yang menguntungkan secara politis dengan mengadu kualitas keislaman para kandidat.
Tentu Komisi Pemilihan Umum tak gegabah mengikuti wacana sensasional yang digulirkan pihak televisi swasta yang targetnya untuk meraih penonton sebanyak mungkin dengan mendiskusikan tema-tema yang memancing reaksi keras baik dari kaum intoleran maupun kelompok toleran itu.
Alih-alih mendialogkan perkara kualitas keislaman kandidat presiden, akan lebih bermanfaat jika televisi swasta itu mengangkat tema bagaimana mencegah lahirnya pribadi-pribadi intoleran bagi pengembangan demokrasi di Tanah Air.
Tokoh-tokoh pembicara yang bisa ditampilkan antara lain kaum moderat maupun militan intoleran baik dari kalangan rohaniman Muslim, Kristiani, Buddhis atau pengikut kepercayaan lain.
Intoleransi sebagai masalah perpolitikan bisa muncul di lingkungan agama apa pun. Dengan kata lain, setiap sistem keimanan dihuni oleh penganut-penganut garis keras, yang tak memberi ruang toleransi bagi kelompok di luar sistem keimanan yang mereka anut.
Intoleransi sesungguhnya merupakan paradoks dalam setiap sistem kepercayaan. Setiap agama mengajarkan kepada pemeluknya bahwa hanya Sang Khalik yang berhak memvonis siapa yang benar dan yang tak benar.
Namun, dalam laku keseharian, apalagi dilandasi oleh seruan politikus yang sedang berkampanye untuk kepentingan politik mereka, ajaran teologis itu terkesampingkan.
Tampaknya, ada salah satu jalan yang bisa digunakan untuk membentengi diri dari kemungkinan terjeblos ke lembah intoleransi itu, yakni membaca sebayak mungkin kisah kehidupan manusia baik dalam bentuk biografi orang terkemuka maupun fiksi sejarah, terutama yang menyangkut konflik keimanan yang berdarah-darah.
Dari biografi atau otobiografi tokoh semacam Mahatma Gandhi, pembaca bisa menemukan hikmah dari eksperimen-eksperimen Gandhi tentang kebenaran. Dilengkapi dengan menyaksikan film kolosal tentang perintis kemerdekaan India itu, seseorang akan menghayati betapa berharganya memiliki sikap mental toleran. Puncak intoleransi hanya melahirkan penderitaan umat manusia.
Pembaca juga bisa mengambil hikmah tentang betapa pentingnya memiliki sikap toleransi lewat buku Kebenaran yang Hilang karya Farag Fouda, intelektuali Mesir, yang berkisah tentang praktik politik dan kekuasaan dalam sejarah kaum Muslim.
Dari buku fiksi, salah satu yang bisa memberikan pencerahan terhadap pembaca adalah novel klasik karya Umberto Eco yang berjudul The Name of Rose. Dari penyajian karya ini, pembaca disuguhi bagaimana sikap-sikap intoleran bisa memunculkan berbagai bentuk kebengisan manusia, yang tak disadari sang pelaku.
Untuk memantapkan pandangan personal tentang betapa pentingnya bersikap toleran kepada orang lain, buku yang layak dicerna adalah teks-teks karya pemikir eksistensialisme semacam Friedrich Nietzsche, Soren Kierkegaard, Jean Paul Sartre dan Dostoyevski.
Memperluas spektrum bacaan dengan menjelajah berbagai aliran filsafat yang paling ekstrem akan menumbuhkan sikap-sikap lapang dada yang pada akhirnya menimbulkan kesadaran personal tentang beragamnya pemikiran manusiawi.
Semakin banyak warga negara yang memiliki penghayatan dan kesadaran tentang keberagaman pemikiran kemanusiaan akan semakin positif bagi pengembangan demokrasi.
Dari keluasan bacaan yang merambah ke berbagai pemikiran hingga yang paling ekstrem inilah, seseorang akan menyadari betapa kompleksnya makna kebenaran.
Ketika seseorang tak dengan mudah mengklaim menemukan dan mengetahui kebenaran, seiring dengan itu tak mudah gegabah pula dia mendaku dirinya sebagai pihak yang paling benar. Di sinilah esensi sikap toleran seorang individu.
Baca juga: Amnesti Internasional: Etnis Uighur diperlakukan diskriminatif
Baca juga: Ratusan pakar kutuk China atas pembangunan pusat penahanan di Xinjiang
Baca juga: China tahan sejuta warga Uighur di fasilitas rahasia
Pewarta: Mulyo Sunyoto
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2018
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2018