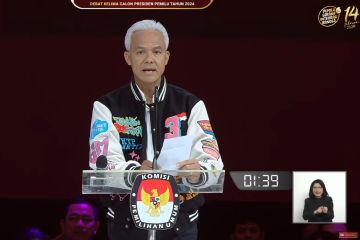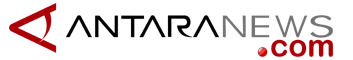Tampaknya kultur yang mencirikan harmoni di sebagian besar kehidupan masyarakat nusantara juga berkontribusi dalam menguatkan tradisi saling menjaga situasi sosial nirkonflik.
Jakarta (ANTARA) - Di hari pencoblosan 17 April ini, sekitar 190 juta warga memberikan suara mereka untuk memilih pemimpin eksekutif dan legislatif dengan harapan akan terwujudnya peningkatan kesejahteraan publik.
Sejak penguasa otokratik-tiranik dilengserkan, sudah empat kali pemilu demokratis terselenggara.
Yang pantas jadi cacatan sejarah adalah bahwa pemilu-pemilu pascareformasi dinilai oleh siapa pun, yakni penyelenggara pemilu, parpol yang terlibat, pengamat internasional independen, bebas dari kecurangan yang sistematis, masif dan terstruktur.
Kecurangan sporadis yang dipicu kesalahpahaman, ditemukannya surat suara yang tercoblos, petugas yang dianggap memihak, memang terjadi di beberapa tempat pemungutan suara, namun dampaknya tak signifikan bagi pemenangan kontestan.
Itu sebabnya, legitimasi pemerintahan yang lahir atas hasil penghitungan suara pada pemilu-pemilu pascareformasi tak dipersoalkan sepanjang lima tahun beroperasinya pemerintahan baru.
Dengan modal sejarah empat pemilu yang berlangsung tanpa gugatan kecurangan secara sistematis, masif dan terstruktur itulah, pemilihan presiden dan anggota legislatif secara serentak yang perdana pada 17 April ini diselenggarakan.
Fakta sejarah itulah yang membuat Wapres Jusuf Kalla berkesimpulan bahwa pencoblosan 17 April 2019 ini pun akan demokratis, aman dan damai tanpa terjadi kecurangan sistematis, masif dan terstruktur.
Baca juga: Warganet cuitkan #TheVictoryofPrabowo dan #JokoWinElection
Kesadaran publik untuk peduli dalam pengawalan pemungutan suara, saling mengawasi, dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Bukan saja semakin tingginya hasrat untuk ikut mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara, tingginya partisipasi dalam mengawal pemilu lewat aplikasi digital pun, seperti yang dikelola kalangan aktivis independen lewat situs Kawal Pemilu juga meningkat.
Jika Kawal Pemilu dioperasikan mulai Pemilu 2014, untuk kali ini, gerakan pengawalan hasil pemungutan suara 2019 ini semakin solid dengan hadirnya Netgrit (Network for Democracy and Electoral Integrity), yang memperkuat gerakan KPJS (Kawal Pemilu-Jaga Suara) 2019.
Pemilu yang terselenggara untuk memilih secara serentak presiden, wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten yang menelan dana sekitar Rp25 triliun itu menjadi pertaruhan seluruh bangsa untuk semakin memantapkan demokrasi, jalan terbaik mengantarkan transisi kekuasaan tanpa kekerasan.
Barangkali yang patut menjadi catatan bagi semua pihak adalah bahwa wacana keamanan yang mengesankan potensi terganggunya keamanan saat pencoblosan masih sering digaungkan, sehingga setiap menjelang pencoblosan lima tahunan pengerahan polisi dan tentara selalu terulang.
Pada Pemilu 2019 ini sebanyak 271.000 polisi, 68.854 personel TNI diterjunkan di tempat-tempat pemungutan suara.
Indikator semakin mantapnya demokrasi bukan saja terukur lewat semakin berkurangnya praktik politik uang, tapi juga semakin minimnya rasa was-was ketidakamanan warga ketika melakukan pencoblosan.
Tentang politik uang, menjelang pencoblosan 2019 ini memang belum sirna sama sekali. Polisi menemukan sejumlah kasus praktik politik uang di sejumlah daerah.
Bahkan KPK juga memproses dugaan politik uang yang cukup fenomenal, dalam bentuk 400 ribu amplop berisi uang yang siap dibagikan di daerah pemilihan Jateng, yang dilakukan caleg dari Partai Golkar.
Dengan penegakan hukum terhadap pelanggar politik uang saat ini, prospek pelanggaran pidana terkait pemilu menjelang pencoblosan di masa depan akan semakin berkurang.
Baca juga: Silent voter sebagai silent killer dalam pesta demokrasi Indonesia
Dari pengalaman empat pemilu pascareformasi, kesadaran warga dalam praktik berdemokrasi yang minus kecurangan secara sistematis, masif dan terstruktur menjadi bukti bahwa berbagai kekhawatiran tentang terjadinya kecurangan yang dinarasikan oleh segelintir elite politik selama masa kampanye hanya pepesan kosong.
Logika semakin mustahilnya kericuhan di saat pencoblosan juga menguat karena fenomena ini: bahwa konflik fisik yang dipicu oleh perbedaan aspirasi politik akan menurun ketika kemerdekaan bersuara atau berekspresi terjamin.
Dalam pemilu 2019 ini, ada diskrepansi realitas yang sangat mencolok antara apa yang terjadi di dunia maya dan dunia nyata.
Gegap gempita antagonisme yang dipicu oleh perbedaan pilihan politik berlangsung di dunia maya namun semua itu tak terefleksikan secara simetris dalam realitas nyata.
Tampaknya kultur yang mencirikan harmoni di sebagian besar kehidupan masyarakat nusantara juga berkontribusi dalam menguatkan tradisi saling menjaga situasi sosial nirkonflik.
Lahirnya generasi milenial yang tak mengenal atau mengalami kekerasan konflik politik juga mendukung lahirnya diskrepansi realitas maya dan nyata.
Fakta-fakta di atas membersitkan prospek gemilang bagi semakin mantapnya praktik demokrasi di masa depan.
Generasi milenial yang akan menjadi pemain utama dalam politik di masa depan mungkin tetap melahirkan hiruk pikuk perbantahan politik di dunia maya namun realitas nyatanya tetap adem ayem seperti yang kini mulai terasakan pada pencoblosan 17 April ini.
Ketika keamanan, kedamaian itu sudah terjelma selama saat-saat pencoblosan, hanya satu perkara yang inti masalahnya berada di pundak elite yang bertarung dalam pencoblosan, khususnya Pilpres 2019 ini.
Yakni kesiapan sang kandidat untuk menerima kekalahan dengan lapang ada, entah setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan sang pemenang atau setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara gugatan hasil Pilpres 2019, andai ada yang menggugat.
Munculnya jiwa kenegarawanan yang berarti kepatuhan pada konstitusi dari capres yang berlaga saat inilah yang berdampak pada semakin mantapnya praktik berdemokrasi di Tanah Air.*
Baca juga: Jokowi optimistis menangi pilpres 2019
Baca juga: Prabowo: Pemilu damai kalau tidak ada kecurangan
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019