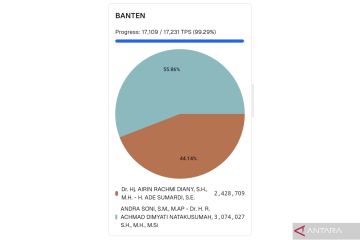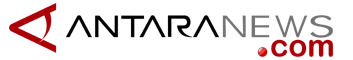Jakarta (ANTARA) - Para pengamat politik memaknai Pemilihan Presiden 2019 dengan menafsirkan sisi pertarungan ideologis di antara kekuatan politik yang terlibat di dalamnya.
Sebagian dari pengamat politik itu berpendapat bahwa yang berkompetisi dalam Pilpres 2019 adalah kekuatan nasionalis melawan kelompok religius, sekalipun faktanya dalam pengubuan yang berlangsung tidak mencerminkan dikotomi murni antara kubu nasionalis versus religius.
Sebagian lagi beropini bahwa Pilpres 2019 sesungguhnya refleksi atas pertarungan kelompok-kelompok religius, lewat dikotomi yang juga tidak murni antara Islam tradisionalis versus Islam modernis.
Dari perspektif pematangan demokrasi, pertarungan yang masih melibatkan kekuatan agamis seperti yang ditafsirkan kalangan pengamat politik itu sesunguhnya tak menjurus ke arah perkembangan politik modern yang ideal.
Konfrontasi politik antara kekuatan nasionalis dan religius tentu mau tak mau akan lebih banyak mengundang wacana-wacana yang kontraproduktif dalam berdemokrasi seperti masih maraknya pengutamaan politik identitas, politisasi agama dan pengagamaan politik.
Padahal, pegiat demokrasi menghendaki kontes politik hanya berkutat ke satu fokus: perang gagasan untuk mengelola negara demi kemakmuran dan membaginya ke rakyat secara adil.
Politik adalah urusan duniawi untuk membahagiakan warga dengan menjamin kebaikan publik, kemerdekaan untuk memburu kebahagian itu tanpa campur tangan berlebihan dari negara. Bila narasi keagamaan menyeruak dalam politik, segmentasi primordial tak terelakkan. Adu gagasan dan program menjadi nomor dua.
Bila tafsir tentang Pilpres 2019 adalah pertarungan Islam tradisionalis versus modernis lebih mendekati kenyataan, kerja lebih keras lagi dari para pegiat demokrasi semakin diperlukan.
Sungguh mencemaskan bila ajang perebutan kuasa politik yang seharusnya semata-mata berdimensi sekuler dalam perspektif demokrasi modern malah menjadi wahana berebut pengaruh antara kelompok-kelompok religius yang benihnya tumbuh sejak pembentukan konstitusi pascakemerdekaan.
Jika Pilpres 2019 ini masih merupakan persaingan tersembunyi antara kelompok riligius tradisionalis versus modernis, tampaknya ada pewarisan konflik ideologis keagamaan dari generasi sebelumnya ke generasi sesudahnya. Namun, tafsir yang sebetulnya bisa dikategorikan muram ini bisa diuji dengan hasil yang akan muncul dalam Pilpres pada 17 April mendatang.
Para pengamat politik melihat kubu Jokowi-Ma'ruf, yang pendukung kelompok religiusnya mayoritas kaum politikus dari latar Islam tradisionalis, berkompetisi melawan kubu Prabowo-Sandi yang pendukung religiusnya mayoritas kaum politikus dari latar belakang Islam modernis.
Dalam konstelasi kekuatan masing-masing kubu sebagaimana terefleksi pada Pilpres 2019 ini, di manakah suara anak-anak muda, generasi milenial yang suaranya cukup signifikan dalam memenangkan pasangan capres-cawapres?
Enigma akan mengalir ke kubu mana suara mayoritas kaum milenial dalam Pilpres 2019 agaknya menarik untuk mengetahui makna terjadinya kontinuitas ataukah disrupsi dalam pertarungan politik yang bermuatan ideologi keagamaan.
Jika kubu petahana menang dalam Pilpres 2019, suara milenial cenderung mengalir ke kubu ini. Artinya, kaum milenial memperkuat basis kekuatan Islam tradisional.
Sebaliknya, bila kubu penantang memenangi Pilpres 2019, mayoritas suara milenial yang mengalir ke kubu ini bisa mengandung makna bahwa ada tendensi terjadinya penguatan basis elektoral di kubu Islam modernis.
Pemaknaan seperti ini tentu mengandung simplifikasi yang riskan untuk dimentahkan lewat hasil penelitian yang lebih seksama dan mendalam dalam melihat beragam variabel.
Apa pun hasil Pilpres 2019, bagi kepentingan pematangan demokrasi di Tanah Air, Pilpres 2024 diharapkan tak lagi ditentukan oleh kekuatan elite politik, tapi oleh arus besar pemilik suara generasi milenial yang lebih melihat politik sebagai urusan duniawi tanpa menyeret-nyeret ideologi keagamaan seperti yang selama ini menjadi karakteristik dalam pertarungan politik lima tahunan.
Situasi global seperti kompetisi ekonomi yang tak berkelindan dengan urusan ideologi keagamaan, kesadaran akan kelangsungan ekologis merupakan faktor ekstrenal yang akan memberi dampak pada menyurutnya dimensi keagamaan dalam pertarungan politik di masa mendatang.
Perkembangan seperti inilah yang memunculkan kemungkinan akan lahirnya partai politik dengan idelogi dasar pro-lingkungan hijau sebagaimana terjadi di sejumlah negara maju meskipun kekuatan parpol yang demikian tak pernah signifikan.
Aktivis politik generasi milenial yang semakin jauh dengan relevansi pertarungan politik aliran/religius di masa lalu bisa menjadi harapan yang menjanjikan bagi kehidupan politik di Tanah Air di masa mendatang, ketika sekularisasi menjadi tak terelakkan.
Biarlah religiusitas menjadi kekuatan batin secara personal yang mendasari keasyikan tiap individu di ruang privat masing-masing, tak perlu diseret ke ranah politik yang sekuler.
Kaum demagog yang masih meramaikan bahkan lebih tepat membuat berisik panggung politik saat ini sudah saatnya mundur untuk digantikan oleh aktor-aktor politik generasi baru yang lebih banyak bicara tentang pertumbuhan ekonomi, penegakan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dan perkara duniawi lainnya.
Seperti yang terjadi di negara demokrasi yang stabil, politik biarlah dikelola secara administratif-managerial untuk memilih manager paling kapabel tanpa mempersoalkan identitas rasial dan religusnya.
Warga London yang rata-rata tercerahkan secara politik tak mempersoalkan politikus Muslim Sadiq Khan yang berasal usul Pakistan menjadi wali kota di negeri salah satu pusat peradaban tertua Eropa itu.
Politik minus ideologi religius itulah yang perlu jadi target bernegara generasi milenial di perhelatan lima tahunan mendatang.
Sebagian dari pengamat politik itu berpendapat bahwa yang berkompetisi dalam Pilpres 2019 adalah kekuatan nasionalis melawan kelompok religius, sekalipun faktanya dalam pengubuan yang berlangsung tidak mencerminkan dikotomi murni antara kubu nasionalis versus religius.
Sebagian lagi beropini bahwa Pilpres 2019 sesungguhnya refleksi atas pertarungan kelompok-kelompok religius, lewat dikotomi yang juga tidak murni antara Islam tradisionalis versus Islam modernis.
Dari perspektif pematangan demokrasi, pertarungan yang masih melibatkan kekuatan agamis seperti yang ditafsirkan kalangan pengamat politik itu sesunguhnya tak menjurus ke arah perkembangan politik modern yang ideal.
Konfrontasi politik antara kekuatan nasionalis dan religius tentu mau tak mau akan lebih banyak mengundang wacana-wacana yang kontraproduktif dalam berdemokrasi seperti masih maraknya pengutamaan politik identitas, politisasi agama dan pengagamaan politik.
Padahal, pegiat demokrasi menghendaki kontes politik hanya berkutat ke satu fokus: perang gagasan untuk mengelola negara demi kemakmuran dan membaginya ke rakyat secara adil.
Politik adalah urusan duniawi untuk membahagiakan warga dengan menjamin kebaikan publik, kemerdekaan untuk memburu kebahagian itu tanpa campur tangan berlebihan dari negara. Bila narasi keagamaan menyeruak dalam politik, segmentasi primordial tak terelakkan. Adu gagasan dan program menjadi nomor dua.
Bila tafsir tentang Pilpres 2019 adalah pertarungan Islam tradisionalis versus modernis lebih mendekati kenyataan, kerja lebih keras lagi dari para pegiat demokrasi semakin diperlukan.
Sungguh mencemaskan bila ajang perebutan kuasa politik yang seharusnya semata-mata berdimensi sekuler dalam perspektif demokrasi modern malah menjadi wahana berebut pengaruh antara kelompok-kelompok religius yang benihnya tumbuh sejak pembentukan konstitusi pascakemerdekaan.
Jika Pilpres 2019 ini masih merupakan persaingan tersembunyi antara kelompok riligius tradisionalis versus modernis, tampaknya ada pewarisan konflik ideologis keagamaan dari generasi sebelumnya ke generasi sesudahnya. Namun, tafsir yang sebetulnya bisa dikategorikan muram ini bisa diuji dengan hasil yang akan muncul dalam Pilpres pada 17 April mendatang.
Para pengamat politik melihat kubu Jokowi-Ma'ruf, yang pendukung kelompok religiusnya mayoritas kaum politikus dari latar Islam tradisionalis, berkompetisi melawan kubu Prabowo-Sandi yang pendukung religiusnya mayoritas kaum politikus dari latar belakang Islam modernis.
Dalam konstelasi kekuatan masing-masing kubu sebagaimana terefleksi pada Pilpres 2019 ini, di manakah suara anak-anak muda, generasi milenial yang suaranya cukup signifikan dalam memenangkan pasangan capres-cawapres?
Enigma akan mengalir ke kubu mana suara mayoritas kaum milenial dalam Pilpres 2019 agaknya menarik untuk mengetahui makna terjadinya kontinuitas ataukah disrupsi dalam pertarungan politik yang bermuatan ideologi keagamaan.
Jika kubu petahana menang dalam Pilpres 2019, suara milenial cenderung mengalir ke kubu ini. Artinya, kaum milenial memperkuat basis kekuatan Islam tradisional.
Sebaliknya, bila kubu penantang memenangi Pilpres 2019, mayoritas suara milenial yang mengalir ke kubu ini bisa mengandung makna bahwa ada tendensi terjadinya penguatan basis elektoral di kubu Islam modernis.
Pemaknaan seperti ini tentu mengandung simplifikasi yang riskan untuk dimentahkan lewat hasil penelitian yang lebih seksama dan mendalam dalam melihat beragam variabel.
Apa pun hasil Pilpres 2019, bagi kepentingan pematangan demokrasi di Tanah Air, Pilpres 2024 diharapkan tak lagi ditentukan oleh kekuatan elite politik, tapi oleh arus besar pemilik suara generasi milenial yang lebih melihat politik sebagai urusan duniawi tanpa menyeret-nyeret ideologi keagamaan seperti yang selama ini menjadi karakteristik dalam pertarungan politik lima tahunan.
Situasi global seperti kompetisi ekonomi yang tak berkelindan dengan urusan ideologi keagamaan, kesadaran akan kelangsungan ekologis merupakan faktor ekstrenal yang akan memberi dampak pada menyurutnya dimensi keagamaan dalam pertarungan politik di masa mendatang.
Perkembangan seperti inilah yang memunculkan kemungkinan akan lahirnya partai politik dengan idelogi dasar pro-lingkungan hijau sebagaimana terjadi di sejumlah negara maju meskipun kekuatan parpol yang demikian tak pernah signifikan.
Aktivis politik generasi milenial yang semakin jauh dengan relevansi pertarungan politik aliran/religius di masa lalu bisa menjadi harapan yang menjanjikan bagi kehidupan politik di Tanah Air di masa mendatang, ketika sekularisasi menjadi tak terelakkan.
Biarlah religiusitas menjadi kekuatan batin secara personal yang mendasari keasyikan tiap individu di ruang privat masing-masing, tak perlu diseret ke ranah politik yang sekuler.
Kaum demagog yang masih meramaikan bahkan lebih tepat membuat berisik panggung politik saat ini sudah saatnya mundur untuk digantikan oleh aktor-aktor politik generasi baru yang lebih banyak bicara tentang pertumbuhan ekonomi, penegakan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dan perkara duniawi lainnya.
Seperti yang terjadi di negara demokrasi yang stabil, politik biarlah dikelola secara administratif-managerial untuk memilih manager paling kapabel tanpa mempersoalkan identitas rasial dan religusnya.
Warga London yang rata-rata tercerahkan secara politik tak mempersoalkan politikus Muslim Sadiq Khan yang berasal usul Pakistan menjadi wali kota di negeri salah satu pusat peradaban tertua Eropa itu.
Politik minus ideologi religius itulah yang perlu jadi target bernegara generasi milenial di perhelatan lima tahunan mendatang.
Pewarta: Mulyo Sunyoto
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019