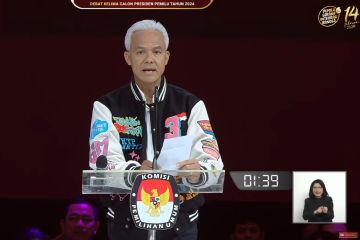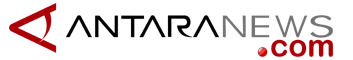Kamus-kamus memaknai asketisme sebagai suatu gaya hidup yang meyakini bahwa kenikmatan duniawi, juga kemewahan dan kemegahannya, adalah jalan sesat menuju pencerahan rohani.
Laku asketik dijalankan oleh para tokoh spiritualis dari berbagai agama besar maupun kecil yang bermazhab bahwa menampik kenikmatan duniawi merupakan jalan terdekat kepada kebenaran ilahi.
Dunia Kristen mengenal Fransiskus Asisi yang menghibahkan kekayaannya dan memiskinkan diri untuk melakoni asketisme. Kisah-kisah sufisme dalam Islam juga mengagungkan laku asketik alias zuhud.
Dalam politik, asketisme dari jenisnya yang natural dan bukan yang ekstrem juga menjadi narasi tersendiri. Dalam sejarah modern, perilaku asketik pada pemimpin politik antara lain diperlihatkan oleh Mahatma Gandhi, yang dipercaya sangat berjasa dalam memerdekakan India dari kolonialisme Inggris.
Bagi politikus di negara-negara berkembang, khususnya yang bergulat dengan problem kemiskinan yang parah, asketisme kadang dipandang sebagai gaya hidup yang diidealkan.
Perdana Menteri Thailand Chuan Lekpai pada periode pertama jabatannya, 23 September 1992 hingga 13 Juli 1995, oleh media-media massa dikisahkan sebagai politikus yang asketis. Pada periode kedua jabatannya sepanjang 9 November 1997 hingga 9 Februari 2001, Lekpai yang tinggal sendiri bahkan dilukiskan oleh majalah Time sebagai politikus yang menyetik alias memasang sendiri kancing jasnya yang copot.
Gambaran kesederhanaan itu membersitkan pesan kepada publik bahwa sang pemimpin adalah sosok yang bukan saja mencintai rakyat kebanyakan, tapi juga menghayati dan menjalankan kehidupan yang bersahaja.
Di era sekarang, ketika keterbukaan semakin menjadi-jadi dan hampir setiap perikehidupan privat para tokoh publik bisa dibocorkan lewat berbagai saluran media massa maupun sosial, penggambaran perilaku asketik politikus akan dengan mudah dibuktikan otentitas.
Dengan demikian, era sekarang bukan hanya populer disebut sebagai zaman berakhirnya kepakaran tapi juga matinya asketisme dalam politik. Tentu bukan kematian absolut, sebab citra asketisme masih bisa disaksikan jejak-jejaknya dalam wujud kehidupan bersahaja, menampik kemegahan, tapi tetap menerima kenyamanan yang dihasilkan kemajuan teknologi.
Sesungguhnya pengaitan asketisme dan politik bisa dilihat sebagai relasi yang paradoksal. Setidak-tidaknya untuk konteks perpolitikan di zaman kapitalisme ini. Bagaimana mungkin menjadi seorang politikus asketik ketika kekuasaan yang diperebutkan itu sudah dikapitalisasi dengan telanjang? Gugatan ini tentu untuk diterapkan kepada para politikus pada umumnya, yang memandang ikhtiar berkuasa adalah untuk mengumpulkan kapital.
Masih ada ruang kekecualian tentunya. Antara lain pada politikus yang terlampau kaya, atau yang sudah lanjut usia seperti Mahathir Mohammad, yang berusia 92 tahun ketika menang dalam perebutan posisi sebagai Perdana Menteri Malaysia tahun lalu.
Di mata publik pemilih, politikus yang terlampau kaya atau sudah lanjut usia pastilah tak punya ambisi lagi untuk memperkaya diri. Itu sebabnya, publik justru memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengelola negara dan keuangannya.
Bagi publik di negara-negara maju kapitalis seperti Amerika Serikat, asketisme politik hampir tak pernah menjadi perhitungan, setidaknya untuk sejarah politik mutakhir mereka.
Yang diidolakan dalam perpolitikan negara kapitalis adalah pemimpin yang sanggup meyakinkan publik bahwa mereka sanggup memakmurkan rakyat zonder memoles-moles karakter privat sang pemimpin, entah sebagai sosok yang baik hati atau sosok yang hidup bersahaja.
Bagaimana dengan perpolitikan di Tanah Air, terutama di momen-momen menjelang pencoblosan 17 April mendatang? Masihkan citra asketisme itu dijadikan instrumen untuk mempersuasi publik pemilih?
Asketisme dalam pengertian yang ekstrem tentu tak lagi digunakan. Namun, para kandidat yang berlaga tetap menjunjung tinggi citra kebersahajaan, kesederhanaan. Seragam putih-putih yang dikenakan Prabowo Subianto sebagai kubu penantang dalam berbagai momen penting jelas membersitkan asosiasi tentang kesahajaan seorang politikus.
Ketika Amien Rais memuji Prabowo dengan mengatakan bahwa raut wajah capres nomor urut 02 itu dipandang dari samping mirip Bung Karno, politikus pendiri Partai Amanat Nasional itu secara implisit hendak mengatakan tentang keagungan dalam kesederhanaan.
Begitu juga dengan Joko Widodo, calon presiden petahana yang dalam berbagai kegiatannya ditonjolkan kesan kesahajaannya. Bukannya mengenakan jaket atau sepatu mahal merek luar negeri, Jokowi ditampilkan merasa senang berbusana dan bersepatu yang harganya bisa dijangkau banyak orang.
Dalam konteks inilah jejak-jejak asketisme dalam politik di Tanah Air masih bisa ditemukan lewat realitas media massa, setidaknya.
Memamerkan kesederhanaan di tengah masyarakat yang sebagian masih bergulat untuk keluar dari lembah kemiskinan adalah keniscayaan dalam perebutan kuasa, di negara berkembang.
Namun, dalam menakar keberhasilan seorang pemimpin politik, unsur kesederhanaan atau kadar asketismenya sama sekali tak signifikan. Di era kelimpahan material dan inovasi yang mengakibatkan pelipatgandaan kapital, kualitas moral pemimpin publik bisa dinomorduakan ketika prestasinya dalam memompa kemakmuran diakui dan terbukti.
Itu sebab para petahana dalam mempertahankan kekuasaannya menghapi sang penantang, di mana pun, sangat perhatian terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi situasi perekonomian menjelang momen pencoblosan.
Dengan demikian, asketisme dalam politik seharusnya bukan saja diabaikan, kalau perlu secara sengaja ditinggalkan, bahkan jejak-jejaknya sekali pun. Pada titik inilah rivalitas politik berfokus kepada kemampuan mengelola negara bukan mengelola kualitas pribadi sang pemimpin.
Baca juga:
Prabowo jalan sehat bersama ribuan relawan Roemah Djoeang
Capres 01: Jabatan saya untuk kebaikan bangsa
Laku asketik dijalankan oleh para tokoh spiritualis dari berbagai agama besar maupun kecil yang bermazhab bahwa menampik kenikmatan duniawi merupakan jalan terdekat kepada kebenaran ilahi.
Dunia Kristen mengenal Fransiskus Asisi yang menghibahkan kekayaannya dan memiskinkan diri untuk melakoni asketisme. Kisah-kisah sufisme dalam Islam juga mengagungkan laku asketik alias zuhud.
Dalam politik, asketisme dari jenisnya yang natural dan bukan yang ekstrem juga menjadi narasi tersendiri. Dalam sejarah modern, perilaku asketik pada pemimpin politik antara lain diperlihatkan oleh Mahatma Gandhi, yang dipercaya sangat berjasa dalam memerdekakan India dari kolonialisme Inggris.
Bagi politikus di negara-negara berkembang, khususnya yang bergulat dengan problem kemiskinan yang parah, asketisme kadang dipandang sebagai gaya hidup yang diidealkan.
Perdana Menteri Thailand Chuan Lekpai pada periode pertama jabatannya, 23 September 1992 hingga 13 Juli 1995, oleh media-media massa dikisahkan sebagai politikus yang asketis. Pada periode kedua jabatannya sepanjang 9 November 1997 hingga 9 Februari 2001, Lekpai yang tinggal sendiri bahkan dilukiskan oleh majalah Time sebagai politikus yang menyetik alias memasang sendiri kancing jasnya yang copot.
Gambaran kesederhanaan itu membersitkan pesan kepada publik bahwa sang pemimpin adalah sosok yang bukan saja mencintai rakyat kebanyakan, tapi juga menghayati dan menjalankan kehidupan yang bersahaja.
Di era sekarang, ketika keterbukaan semakin menjadi-jadi dan hampir setiap perikehidupan privat para tokoh publik bisa dibocorkan lewat berbagai saluran media massa maupun sosial, penggambaran perilaku asketik politikus akan dengan mudah dibuktikan otentitas.
Dengan demikian, era sekarang bukan hanya populer disebut sebagai zaman berakhirnya kepakaran tapi juga matinya asketisme dalam politik. Tentu bukan kematian absolut, sebab citra asketisme masih bisa disaksikan jejak-jejaknya dalam wujud kehidupan bersahaja, menampik kemegahan, tapi tetap menerima kenyamanan yang dihasilkan kemajuan teknologi.
Sesungguhnya pengaitan asketisme dan politik bisa dilihat sebagai relasi yang paradoksal. Setidak-tidaknya untuk konteks perpolitikan di zaman kapitalisme ini. Bagaimana mungkin menjadi seorang politikus asketik ketika kekuasaan yang diperebutkan itu sudah dikapitalisasi dengan telanjang? Gugatan ini tentu untuk diterapkan kepada para politikus pada umumnya, yang memandang ikhtiar berkuasa adalah untuk mengumpulkan kapital.
Masih ada ruang kekecualian tentunya. Antara lain pada politikus yang terlampau kaya, atau yang sudah lanjut usia seperti Mahathir Mohammad, yang berusia 92 tahun ketika menang dalam perebutan posisi sebagai Perdana Menteri Malaysia tahun lalu.
Di mata publik pemilih, politikus yang terlampau kaya atau sudah lanjut usia pastilah tak punya ambisi lagi untuk memperkaya diri. Itu sebabnya, publik justru memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengelola negara dan keuangannya.
Bagi publik di negara-negara maju kapitalis seperti Amerika Serikat, asketisme politik hampir tak pernah menjadi perhitungan, setidaknya untuk sejarah politik mutakhir mereka.
Yang diidolakan dalam perpolitikan negara kapitalis adalah pemimpin yang sanggup meyakinkan publik bahwa mereka sanggup memakmurkan rakyat zonder memoles-moles karakter privat sang pemimpin, entah sebagai sosok yang baik hati atau sosok yang hidup bersahaja.
Bagaimana dengan perpolitikan di Tanah Air, terutama di momen-momen menjelang pencoblosan 17 April mendatang? Masihkan citra asketisme itu dijadikan instrumen untuk mempersuasi publik pemilih?
Asketisme dalam pengertian yang ekstrem tentu tak lagi digunakan. Namun, para kandidat yang berlaga tetap menjunjung tinggi citra kebersahajaan, kesederhanaan. Seragam putih-putih yang dikenakan Prabowo Subianto sebagai kubu penantang dalam berbagai momen penting jelas membersitkan asosiasi tentang kesahajaan seorang politikus.
Ketika Amien Rais memuji Prabowo dengan mengatakan bahwa raut wajah capres nomor urut 02 itu dipandang dari samping mirip Bung Karno, politikus pendiri Partai Amanat Nasional itu secara implisit hendak mengatakan tentang keagungan dalam kesederhanaan.
Begitu juga dengan Joko Widodo, calon presiden petahana yang dalam berbagai kegiatannya ditonjolkan kesan kesahajaannya. Bukannya mengenakan jaket atau sepatu mahal merek luar negeri, Jokowi ditampilkan merasa senang berbusana dan bersepatu yang harganya bisa dijangkau banyak orang.
Dalam konteks inilah jejak-jejak asketisme dalam politik di Tanah Air masih bisa ditemukan lewat realitas media massa, setidaknya.
Memamerkan kesederhanaan di tengah masyarakat yang sebagian masih bergulat untuk keluar dari lembah kemiskinan adalah keniscayaan dalam perebutan kuasa, di negara berkembang.
Namun, dalam menakar keberhasilan seorang pemimpin politik, unsur kesederhanaan atau kadar asketismenya sama sekali tak signifikan. Di era kelimpahan material dan inovasi yang mengakibatkan pelipatgandaan kapital, kualitas moral pemimpin publik bisa dinomorduakan ketika prestasinya dalam memompa kemakmuran diakui dan terbukti.
Itu sebab para petahana dalam mempertahankan kekuasaannya menghapi sang penantang, di mana pun, sangat perhatian terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi situasi perekonomian menjelang momen pencoblosan.
Dengan demikian, asketisme dalam politik seharusnya bukan saja diabaikan, kalau perlu secara sengaja ditinggalkan, bahkan jejak-jejaknya sekali pun. Pada titik inilah rivalitas politik berfokus kepada kemampuan mengelola negara bukan mengelola kualitas pribadi sang pemimpin.
Baca juga:
Prabowo jalan sehat bersama ribuan relawan Roemah Djoeang
Capres 01: Jabatan saya untuk kebaikan bangsa
Pewarta: Mulyo Sunyoto
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019