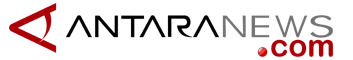Sikap yang paling demokratis terhadap fenomena golput adalah netralJakarta (ANTARA News) - Sebagian besar dari mereka yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum namun secara sadar tak menggunakan haknya saat hari pencoblosan pada hakikatnya bukan warga negara yang apatis secara politis.
Mereka, yang dalam konteks perpolitikan di Tanah Air disebut atau menyebut diri sebagai golongan putih alias golput, justru punya perhitungan politis ideologis yang matang ketika memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya saat pencoblosan.
Golput dipopulerkan kalangan aktivis menjelang Pemilu 1971. Salah satu pelopornya, Arief Budiman, berpandangan bahwa pemilu di bawah rezim Orde Baru yang militeristik tak bisa dipercaya sebagai mekanisme demokrasi karena sarat manipulasi.
Angka-angka yang dikeluarkan penguasa Orba untuk partisipasi warga negara dalam Pemilu 1971 memperlihatkan bahwa perlawanan kaum golput nyaris tak bermakna.
Jumlah persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya diklaim penguasa sebanyak 96,6 persen, sedangkan yang memilih golput di angka 3,4 persen.
Selanjutnya, seruan untuk golput menjelang Pemilu 1977 hingga Pemilu 1997, sebelum Orde Baru tumbang, tetap terdengar meski tak seintens menjelang Pemilu 1971.
Memasuki era Reformasi, pada Pemilu 1999 yang dipandang sebagai pemilu yang lebih demokratis dibandingkan dengan pemilu di bawah Orba, seruan untuk menjadi golput boleh dibilang raib.
Bahkan, kalangan aktivis prodemokrasi memproklamasikan bahwa golput sudah tak relevan lagi.
Namun, sepuluh tahun kemudian, saat Pemilu 2009, tanpa ada gerakan golput, tingkat golput ternyata cukup tinggi.
Menurut data yang dicatat Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gajah Mada, tingkat golput pada Pemilu 2009 mencapai 39,1 persen.
Baca juga: Debat capres diharapkan turunkan angka golput
Menurut sejumlah pakar politik, tingginya golput pada Pemilu 2009 diakibatkan oleh persoalan teknis nonideologis-politis, seperti banyaknya pemilih yang tak memenuhi persyarakatan administratif saat pencoblosan, juga oleh faktor ketidakpercayaan pemilih kepada para politikus, calon anggota legislatif yang mereka anggap tak amanah.
Berapakah potensi golput pada Pileg dan Pilpres 2019 ini? Lembaga riset jajak pendapat Indikator Politik Indonesia memprediksi jumlahnya sekitar 20 persen, tak jauh berbeda dengan tingkat golput pada Pilpres 2014 yang mencapai 24,89 persen.
Persepsi publik terhadap kaum golput di Tanah Air agaknya tak lepas dari stigma yang ditanamkan penguasa Orde Baru terhadap mereka. Bahkan, setelah era Reformasi, masih ada kelompok ulama yang mengeluarkan pernyataan bahwa menjadi golput itu haram.
Seruan untuk menggunakan hak pilih yang digaungkan oleh para politikus dari kedua kubu koalisi yang berkompetisi dalam Pilpres 2019 lebih membahana dibandingkan dengan ajakan untuk menjadi golput.
Yang cukup menghebohkan namun tak mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi adalah gencarnya caci maki terhadap kaum golput yang dilontarkan salah satu pendukung kubu koalisi dengan tuduhan bahwa golput disuarakan oleh kubu lawan untuk strategi pemenangan.
Argumen penuduh menjadi gugur begitu ada fakta bahwa kedua koalisi parpol pengusung pasangan calon presiden-wakil presiden sama-sama menyerukan pemilih untuk tidak menjadi golput pada Pilpres 2019.
Sikap yang paling demokratis terhadap fenomena golput adalah netral, tidak memasakan diri menyerukan warga untuk memilih atau tidak mengecam mereka yang memilih menjadi golput.
Dalam literatur dasar ilmu politik, mahasiswa memperoleh pengetahuan bahwa tingkat partisipasi warga negara dalam pemilihan umum di negara-negara yang demokratis jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang di bawah penguasa otoriter-tiranik.
Baca juga: Advokat publik sebut golput sebagai bentuk protes
Tingginya tingkat partisipasi pemilu di negara yang dikuasi oleh rezim otokratik diakibatkan oleh mobilisasi yang dilakukan aparat negara terhadap warga, baik dengan intimidasi maupun dengan strategi politik uang.
Di bawah rezim Orba, mereka yang memilih golput tak diapa-apakan oleh penguasa namun secara personal ada perasaan tak nyaman dengan pertimbangan harmoni sosial.
Itu sebabnya, di bawah rezim otoriter, golput dilakukan bukan dengan mangkir tidak mendatangi tempat-tempat pemungutan suara tapi dengan cara tetap mendatangi tempat pencoblosan tapi tanpa mencoblos atau mencoblos secara tidak sah pada surat suara.
Ketika sistem pencoblosan belum didukung teknologi yang semakin maju, jumlah golput yang diakibatkan alasan teknis, seperti harus pulang ke kampung halaman dari tempat kuliah di kota lain untuk mencoblos, cukup tinggi.
Kini alasan teknis seperti itu semakin tereduksi oleh perbaikan sistem pencoblosan.
Tampaknya, sikap-sikap naif terhadap kaum golput sudah saatnya diakhiri. Maraknya caci-maki yang dilontarkan di akun-akun media sosial oleh warganet terhadap mereka yang berniat untuk menjadi golput mencerminkan bahwa sikap demokrat masih perlu ditumbuhkan.
Ada perkembangan menarik yang bisa dicatat tentang kiprah kaum ulama menjelang Pilpres 2019.
Alih-alih mengecam kaum golput atau mengharamkam tindakan golput, kaum ulama yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam yang dipimpin Said Aqil Siroj berkomitmen untuk mengawal jalannya Pemilu 2019.
Apa makna mengawal di sini? Ini bisa berupa keterlibatan untuk menjaga proses pemilu berlangsung secara demokratis.
Dengan kekuatan moralnya yang direspek oleh umat, para ulama ambil bagian untuk menjaga agar Pilpres 2019 bebas dari kecurangan atau manipulasi dalam berbagai bentuknya.
Baca juga: KPU diminta giatkan sosialisasi pilkada cegah golput
Baca juga: LBH Jakarta prediksi pemilih golput meningkat di Pilpres 2019
Pewarta: Mulyo Sunyoto
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019