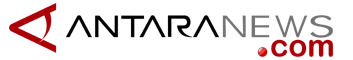Jakarta (ANTARA News) - Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) menyatakan bahwa ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1); ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2);
”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3); dan ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4).
Namun pada kenyataannya implementasi pasal-pasal tersebut tidak mudah.
Team Leader Human Right Defender dari Kemitraan Ririn Sefsani ditemui saat media briefing koalisi Golongan Hutan di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (15/2), mengatakan untuk melepaskan calon presiden (capres) dari kepentingan yang akhirnya dapat merugikan keberlanjutan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan maka, pertama, jika melihat dari sisi partai politik (parpol) maka harus direformasi total, mengingat saat ini di Indonesia sistem dinasti kuat sekali.
Kedua, tidak ada satu partai pun yang menjalankan fungsi kepartaiannya dalam konteks pendanaan. Dari hasil pemetaan Kemitraan terhadap semua parpol, tidak ada satu pun yang menunjukkan bahwa anggotanya menyetor iuran. Lalu parpol juga tidak melakukan akuntabilitas kepada publik tentang sumber-sumber pendanaannya.
Ketiga, ada dorongan skema pemberian alokasi APBN kepada parpol. Kemitraan sudah mendiskusikan ini dengan KPK, bahwa tata kelola keuangan yang menjadi bagian reformasi dalam tubuh parpol harus dilaksanakan dengan melakukan transparansi, sehingga negara bisa memberikan alokasi dana lebih kepada mereka.
Keempat, terkait oligarki, akan sulit mencari siapa pengusaha yang mendukung capres tertentu dalam bukti otentik sumber-sumber yang diberikan mengingat mereka melakukannya di bawah tangan.
Kelima, biaya elektoral mahal karena reformasi parpol tidak dijalankan. Partai gagal melakukan pendidikan politik pada calon anggotanya.
Banyak kader-kader baik yang lahir dari parpol, tapi dikalahkan oleh oligarki dan dinasti. Menurut Ririn, ini salah satu sisi praktik politik kotor, dalam hal ini dukungan biaya kampanye, biaya uang dan biaya beli kursi masih terjadi.
Jika dua capres benar-benar mau melakukan reformasi maka transparansi harus dilakukan dengan membuka kepada publik siapa-siapa saja pengusaha yang mendukung mereka. Dengan demikian masyarakat akan didorong untuk melacak, misalnya siapa pengusaha-pengusaha besar yang disinyalir banyak bermain di belakang calon.
Ini, menurut dia, menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan parpol dan penyelenggara Pemilu, karena tidak semua caleg juga mau menyerahkan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPN) kepada KPK.
“Ini wajah nyata bagaimana oligarki dan intransparansi elit politik di dalam konstelasi Pilpres (Pemilihan Presiden) dan Pileg (Pemilihan Legislatif),” kata Ririn.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menurut dia, harus punya peran besar dalam meminta dan melaporkan dana-dana kampanye.
Normatif administrasi di bawah undang-undang memang memungkinkan secara pribadi seseorang bisa menyumbang dana kampanye dalam jumlah tertentu, tapi masyarakat awam pun harus bisa menilai berapa dana yang mengalir, ujar dia.
Ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas tidak terbangun sama sekali dalam konstelasi Pemilu.
Kemitraan yang bekerja dengan parpol dan politisi di parlemen, ia mengatakan, mendapat pula pernyataan-pernyataan dari kader-kader parpol muda tentang siapa yang tidak bisa mengatakan bahwa partai tersebut dimiliki pengusaha.
Menurut Ririn, mereka mengatakan bisa saja melakukan perubahan tapi kondisi di parpol seperti leher botol, di bawah boleh berinovasi apapun tapi begitu sampai di atas tentu diserahkan pada elit di Dewan Pengurus Pusat (DPP) atau “who behind them”, artinya adalah para pengusaha atau aktor-aktor yang punya uang banyak.
Ini, lanjutnya, menjadi tantangan untuk membangun pemerintahan yang baik. Selama tidak ada reformasi di parpol tidak akan maju.
“Mana ada aktivis seperti kami bisa bersaing maju berpolitik, yang ada malah terseret dalam pusaran politik elit. Ini pengalaman kita dari 2009 dan 2014,” ujar dia.
Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan kalau di Amerika Serikat (AS), presiden terpilih juga akan membawa tim ke Gedung Putih. Tapi political financing di sana jauh lebih tertata, karena jika ada tim lobi, itu akan terdata sehingga publik AS bisa memantau bahwa mereka bukan di “wilayah gelap” atau di balik layar.
Sedangkan di Indonesia, lanjutnya, dana kampanye yang didaftar di KPU diketahui, tapi tidak perlu ahli roket untuk menghitung bahwa sebenarnya dana kampanyenya yang dikeluarkan berkali-kali lipat dari yang terdaftar.
“Jadi kontestasi politik kita mahal sekali. Nanti ujung-ujungnya ada balas budi,” ujar Leo.
Jika melihat Barrack Obama saat menjadi Presiden AS, Leo mengatakan relatif bisa membuat tim West Wing Gedung Putih dan kementerian dengan pemilihan figur yang bersih dari kait-mengkait dana kampanye.
Ujung-ujungnya keberanian. Menurut dia, presiden terpilih nanti seharusnya berani memilih tim yang bersih, bukan berdasar pada balas budi.
Benahi tata kelola
Reformasi birokrasi menjadi perhatian penting yang, menurut Ririn, harus dilakukan di eksekutif. Contoh yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah pembenahan untuk transparansi dan akuntabilitas perizinan dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.
Untuk perizinan terkait SDA, menurut dia, permainan di bawah meja perlu diawasi. Perlu ada investigasi khusus dilakukan beberapa pihak untuk mengetahui kemungkinan adanya permainan tersebut, namun ancaman bagi pembela lingkungan juga tinggi.
Ririn melihat dari dua capres yang maju dalam Pilpres 2019 masih menempatkan SDA dan lingkungan sebagai bagian sumber ekonomi. Jadi harapannya hanya siapapun yang terpilih bisa memperbaiki tata kelola izin.
“Sekarang bisa dibayangkan Kalimantan Barat itu luas wilayah sama izin sawitnya lebih besar izin sawitnya, itu kan gila,” ujar Ririn.
Harus dipaparkan tata ruang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perizinan juga diperbaiki di semua level pemerintah pusat dan daerah, lalu tata kelola di kelembagaan juga masih perlu dibenahi koordinasinya.
“Saya capek, tujuh tahun mengerjakan isu Reformasi Birokrasi, koordinasi tidak jalan karena mereka miliki kepentingan sendiri-sendiri. Kalau di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berusaha melindungi meski ada juga izin yang keluar, di Kementerian ESDM ada kepentingan ekonomi,” kata Ririn.
Ini, menurut dia, siapapun yang terpilih perlu melakukan reformasi di kelembagaan supaya masyarakat tahu tidak ada lagi over lapping atau ego sektoral.
Soal “One Map, One Policy” belum jadi juga. Dulu di Bappenas sempat akan ada khusus biro atau kedeputian yang menyinkronisasi semua kebijakan.
“Tapi apakah Bappenas membawahi semua Kementerian/Lembaga? Nah ini juga pekerjaan rumah, dia harus lembaga khusus bersifat “ad hoc” dengan mandatori maksimal dua tahun membenahi semua kebijakan yang carut-marut, bekerja di bawah presiden,” ujar dia.
Jadi mulai dari Pusat hingga daerah, dan semua Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah hingga desa harus tunduk atas harmonisasi dari pembenahan kebijakan bermasalah dan saling bertentangan, lanjutnya.
Jika ini tidak dilakukan maka, menurut Ririn, akan berulang. Persoalan tata kelola dan ego sektoral akan tetap sama siapapun yang akan memimpin Indonesia nantinya.
Dalam UUD 1945, ia mengatakan sudah secara jelas menyebutkan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikelola untuk kemakmuran rakyat. Yang terjadi justru privatisasi air, privatisasi yang lain, sehingga secara konstitusi itu sudah melanggar.
Baca juga: Debat capres diharapkan pengaruhi pemilih
Baca juga: Jelang debat Presiden Jokowi lari pagi di Kebun Raya Bogor
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019