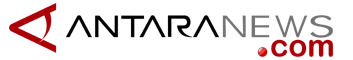Dalam diskusi tentang kapabilitas capres dan media massa, seorang pengamat politik mengatakan, sikap keras terhadap media yang diperlihatkan oleh calon presiden bisa memengaruhi kadar kebebasan bila calon itu menang dalam Pilpres 2019.
Konkretnya, capres yang selama masa kampanye memperlihatkan permusuhan terhadap awak media, alih-alih menjadi mitra kerja, diprediksi akan menjalankan kebijakan yang cenderung mengekang kemerdekaan pers.
Prediksi itu tentu perlu diuji probabilitasnya, peluang kesesuaiannya dengan realitas. Setiap penguasa memang cenderung mengukuhkan kekuasaanya dengan segala cara, antara lain membatasi kebebasan media.
Namun, ketika sistem politik yang beroperasi, yang membingkai kerja penguasa itu terselenggara secara demokratis, apalagi dalam kondisi kemerdekaan berekspresi secara global saat ini, yang dipicu oleh maraknya berbagai saluran media sosial yang hampir mustahil dikekang, sikap keras terhadap media tak akan mengurangi kemerdekaan pers.
Amerika adalah contoh mutakhir dengan naiknya pebisnis properti terkemuka Donald Trump sebagai presiden. Setelah sukses menduduki kursi kepresidenan, Trump memperlihatkan sikap permusuhan terhadap media massa. Pernyataan-pernyataannya yang disampaikan lewat akun Twitternya tentang pers yang dinilainya sebagai musuh masyarakat mendapat cemooh dari berbagai kalangan.
Trump juga sempat membatasi akses wartawan-wartawan dari media terkemuka untuk meliput kegiatannya di Gedung Putih. Hanya media yang dinilai tak merugikannya yang diperbolehkan meliput kegiatannya.
Tampaknya hanya sebatas sikap diskriminatif semacam itulah yang bisa dilakukan presiden terhadap media massa.
Kebebesan berekspresi yang dinikmati pers di Indonesia pascareformasi 1998 telah ditopang oleh konstitusi dan berbagai undang-undang yang tak memungkinkan lagi terjadi pembredelan seperti era Orba.
Sekalipun pemerintah bisa melahirkan regulasi untuk membatasi kebebasan pers dengan berbagai kiat, keberagaman dan banyaknya saluran berekspresi yang dilahirkan oleh teknologi informasi akan memorakporandakan soliditas dalam menekan kebebasan pers.
Sebelum muncul media sosial, media bawah tanah, pamplet, karya sastra menyuarakan perlawanan kepada penguasa ketika media arus utama diberangus. Kekuatan subversif selalu bermunculan di mana-mana, di ruang-ruang pentas teater, pembacaan puisi, atau di selebaran gelap seperti risalah Independen di saat menjelang Reformasi di Tanah Air.
Dengan munculnya media sosial yang terlalu digdaya untuk diberangus, semakin sia-sialah sikap keras penguasa terhadap media massa. Tindakan Trump yang diskriminatif terhadap media hanya melahirkan paradoks. Unggahannya di Twitter bukan saja dijadikan bahan kritik oleh pengamat politik, cendekiawan tapi juga mengundang caci maki dari rakyat awam yang tak bersimpati kepadanya.
Apa yang bisa diperbuat oleh presiden untuk memusuhi media massa yang menjadi pilar demokrasi? Paling banter ya menutup akses liputan resmi kegiatan sang presiden buat sejumlah media yang dianggap sebagai musuhnya.
Namun, sikap diskriminatif ini justru menjadi bahan bakar bagi para editor media yang dimusuhi itu untuk memuat tulisan-tulisan yang pedas mengkritik sang presiden. Itu bisa dilakukan dengan menulis di halaman tajuk dan opini.
Ironisnya, media yang dimusuhi pemerintah inilah yang akan diminati oleh pembaca. Pemeo bahwa berita negatif adalah berita positif atau berita yang mengungkap keburukan adalah berita yang menantang untuk dibaca, mengakibatkan sikap menganaktirikan media justru jadi berkah bagi media bersangkutan.
Realitas demikainlah yang memungkinkan bahwa sikap keras capres terhadap media selama kampanye tidak selalu diikuti oleh kecenderungan untuk surutnya kebebasan media ketika capres itu menang dalam pilpres.
Ada prediksi kedua, yang dilontarkan oleh awak media sendiri bahwa sikap keras terhadap media yang diperlihatkan capres menjelang pilpres itu semata-mata sebagai bagian dari strategi kampanye. Artinya sikap itu secara sadar dipilih untuk membangun citra bahwa sang kandidat tak mau mengekor citra pesaingnya yang menjadi kesayangan awak media umumnya.
Perkiraan kedua inilah yang paling mungkin mendekati realita. Sayangnya sang awak media itu tak meramal lebih jauh apakah sang kandidat yang keras terhadap media itu akan tetap bersikap keras atau melunak bila dia meraih kemenangan dalam pilpres.
Setiap capres pasti dikelilingi para pakar di berbagai bidang, sehingga setiap sikap dan tindakan verbalnya terhadap setiap isu atau wacana senantiasa dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan para pakar yang menjadi bagian dari tim pemenangannya.
Pembatasan terhadap kebebasan pers hanya efektif di situasi yang memungkinkan kekuasaan yang monolitik sanggup menguasai publik secara total. Saat ini tinggal beberapa gelintir negara yang penguasanya menikmati tolalitarianisme politik itu.
Indonesia sudah berada di titik yang tak mungkin dibalikkan ke masa silam yang totaliter-tiranik seperti era Orba. Siapa pun presidennya, masa depan yang diwarnai kebebasan berekspresi harus menjadi paradigma untuk memerintah.
Untuk mengonsolidasikan kekuatan politik, pemerintah hanya bisa merangkul sebagian pemilik media yang berafiliasi dengan parpol yang mendukungnya. Ketika semua media besar berhimpun di kelompok oligarkhis seperti itu, media-media di luarnya, yang tak terhitung jumlahnya meskipun berskala kecil, akan menjadi kekuatan pengganggu dan selalu punya potensi untuk menggoyang oligarkhi media arus utama yang segaris dengan pemerintah.
Di sinilah titik lemah prediksi bahwa kebebasan pers akan diperlemah oleh naiknya capres yang memperlihatkan sikap kerasnya terhadap media. Angin kekebasan tampaknya terlalu kencang !
Baca juga: Peneliti: Media harus bisa jadi acuan saat pemilu
Konkretnya, capres yang selama masa kampanye memperlihatkan permusuhan terhadap awak media, alih-alih menjadi mitra kerja, diprediksi akan menjalankan kebijakan yang cenderung mengekang kemerdekaan pers.
Prediksi itu tentu perlu diuji probabilitasnya, peluang kesesuaiannya dengan realitas. Setiap penguasa memang cenderung mengukuhkan kekuasaanya dengan segala cara, antara lain membatasi kebebasan media.
Namun, ketika sistem politik yang beroperasi, yang membingkai kerja penguasa itu terselenggara secara demokratis, apalagi dalam kondisi kemerdekaan berekspresi secara global saat ini, yang dipicu oleh maraknya berbagai saluran media sosial yang hampir mustahil dikekang, sikap keras terhadap media tak akan mengurangi kemerdekaan pers.
Amerika adalah contoh mutakhir dengan naiknya pebisnis properti terkemuka Donald Trump sebagai presiden. Setelah sukses menduduki kursi kepresidenan, Trump memperlihatkan sikap permusuhan terhadap media massa. Pernyataan-pernyataannya yang disampaikan lewat akun Twitternya tentang pers yang dinilainya sebagai musuh masyarakat mendapat cemooh dari berbagai kalangan.
Trump juga sempat membatasi akses wartawan-wartawan dari media terkemuka untuk meliput kegiatannya di Gedung Putih. Hanya media yang dinilai tak merugikannya yang diperbolehkan meliput kegiatannya.
Tampaknya hanya sebatas sikap diskriminatif semacam itulah yang bisa dilakukan presiden terhadap media massa.
Kebebesan berekspresi yang dinikmati pers di Indonesia pascareformasi 1998 telah ditopang oleh konstitusi dan berbagai undang-undang yang tak memungkinkan lagi terjadi pembredelan seperti era Orba.
Sekalipun pemerintah bisa melahirkan regulasi untuk membatasi kebebasan pers dengan berbagai kiat, keberagaman dan banyaknya saluran berekspresi yang dilahirkan oleh teknologi informasi akan memorakporandakan soliditas dalam menekan kebebasan pers.
Sebelum muncul media sosial, media bawah tanah, pamplet, karya sastra menyuarakan perlawanan kepada penguasa ketika media arus utama diberangus. Kekuatan subversif selalu bermunculan di mana-mana, di ruang-ruang pentas teater, pembacaan puisi, atau di selebaran gelap seperti risalah Independen di saat menjelang Reformasi di Tanah Air.
Dengan munculnya media sosial yang terlalu digdaya untuk diberangus, semakin sia-sialah sikap keras penguasa terhadap media massa. Tindakan Trump yang diskriminatif terhadap media hanya melahirkan paradoks. Unggahannya di Twitter bukan saja dijadikan bahan kritik oleh pengamat politik, cendekiawan tapi juga mengundang caci maki dari rakyat awam yang tak bersimpati kepadanya.
Apa yang bisa diperbuat oleh presiden untuk memusuhi media massa yang menjadi pilar demokrasi? Paling banter ya menutup akses liputan resmi kegiatan sang presiden buat sejumlah media yang dianggap sebagai musuhnya.
Namun, sikap diskriminatif ini justru menjadi bahan bakar bagi para editor media yang dimusuhi itu untuk memuat tulisan-tulisan yang pedas mengkritik sang presiden. Itu bisa dilakukan dengan menulis di halaman tajuk dan opini.
Ironisnya, media yang dimusuhi pemerintah inilah yang akan diminati oleh pembaca. Pemeo bahwa berita negatif adalah berita positif atau berita yang mengungkap keburukan adalah berita yang menantang untuk dibaca, mengakibatkan sikap menganaktirikan media justru jadi berkah bagi media bersangkutan.
Realitas demikainlah yang memungkinkan bahwa sikap keras capres terhadap media selama kampanye tidak selalu diikuti oleh kecenderungan untuk surutnya kebebasan media ketika capres itu menang dalam pilpres.
Ada prediksi kedua, yang dilontarkan oleh awak media sendiri bahwa sikap keras terhadap media yang diperlihatkan capres menjelang pilpres itu semata-mata sebagai bagian dari strategi kampanye. Artinya sikap itu secara sadar dipilih untuk membangun citra bahwa sang kandidat tak mau mengekor citra pesaingnya yang menjadi kesayangan awak media umumnya.
Perkiraan kedua inilah yang paling mungkin mendekati realita. Sayangnya sang awak media itu tak meramal lebih jauh apakah sang kandidat yang keras terhadap media itu akan tetap bersikap keras atau melunak bila dia meraih kemenangan dalam pilpres.
Setiap capres pasti dikelilingi para pakar di berbagai bidang, sehingga setiap sikap dan tindakan verbalnya terhadap setiap isu atau wacana senantiasa dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan para pakar yang menjadi bagian dari tim pemenangannya.
Pembatasan terhadap kebebasan pers hanya efektif di situasi yang memungkinkan kekuasaan yang monolitik sanggup menguasai publik secara total. Saat ini tinggal beberapa gelintir negara yang penguasanya menikmati tolalitarianisme politik itu.
Indonesia sudah berada di titik yang tak mungkin dibalikkan ke masa silam yang totaliter-tiranik seperti era Orba. Siapa pun presidennya, masa depan yang diwarnai kebebasan berekspresi harus menjadi paradigma untuk memerintah.
Untuk mengonsolidasikan kekuatan politik, pemerintah hanya bisa merangkul sebagian pemilik media yang berafiliasi dengan parpol yang mendukungnya. Ketika semua media besar berhimpun di kelompok oligarkhis seperti itu, media-media di luarnya, yang tak terhitung jumlahnya meskipun berskala kecil, akan menjadi kekuatan pengganggu dan selalu punya potensi untuk menggoyang oligarkhi media arus utama yang segaris dengan pemerintah.
Di sinilah titik lemah prediksi bahwa kebebasan pers akan diperlemah oleh naiknya capres yang memperlihatkan sikap kerasnya terhadap media. Angin kekebasan tampaknya terlalu kencang !
Baca juga: Peneliti: Media harus bisa jadi acuan saat pemilu
Pewarta: Mulyo Sunyoto
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019