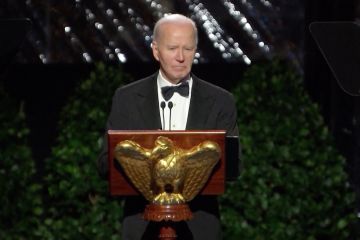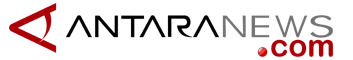Ada dua titik ekstrem yang tak dikehendaki dalam menyongsong Pemilihan Presiden 2019, yakni intensifnya kadar fanatisme pemilih di satu sisi, dan tingginya tingkat apatisme pemilik hak suara.
Kekhawatiran atas munculnya dua fenomena sosial itu berulang kali dilontarkan berbagai kalangan yang berkepentingan dengan berlangsungnya pemilihan presiden yang demokratis, dengan hasil yang absah sehingga diterima oleh kontestan yang berkompetisi.
Fanatisme pemilih antara lain diperlihatkan oleh semakin kerasnya perang verbal di dunia maya yang melibatkan dua pendukung fanatik masing-masing kubu, yakni kubu petahana dan kubu penantang.
Jika fanatisme itu murni bermuatan anasir politis ideologis, persoalannya relatif akan lebih mudah diurai dan ditangani. Namun, ketika fanatisme itu berkelindan dengan aspek keimanan, identitas keagamaan pemilih, problemnya semakin kusut dan semakin sulit untuk mengatasinya. Setidaknya, bukan saja pendekatan politik yang dibutuhkan tapi juga pendekatan kultural-keagamaan diperlukan untuk mengatasinya. Politikus pun perlu bantuan tokoh agama untuk menyelesaikan masalah itu.
Yang menarik dalam Pilpres 2019 adalah warna ideologis perkubuan yang terbentuk, sebagai refleksi kepentingan politik pragmatis masing-masing koalisi. Yang terjadi bukannya kontes atau rivalitas politik antara kekuatan partai politik yang nasionalis berhadapan dengan parpol yang menonjol ideologi keagamaannya.
Hal ini jelas menguntungkan dari sisi upaya meredakan intensitas persaingan sengit di antara kubu-kubu yang bersaing. Bisa dibayangkan betapa destruktif akibatnya jika parpol nasionalis seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Berkarya berhadapan dengan koalisi yang terdiri atas parpol yang secara historis beranasir keagamaan, setidaknya beridentitas keagamaan, seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.
Sekalipun koalisi yang terbentuk bersifat heterogen dalam arti campuran antara parpol yang beridentitas kebangsaan dan keberagamaan, nyatanya dalam politik riil yang terjadi tetaplah munculnya kampanye yang menggunakan simbol-simbol keagamaan, selain lambang-lambang yang berkaitan dengan sekularitas.
Dari kompleksitas yang demikianlah, publik pemilih mendapat suguhan wacana tentang dikotomi parpol setan dan parpol tuhan, yang kemudian diikuti pula narasi yang menistakan pemimpin yang kafir, dikonfrontasikan dengan pemimpin yang sesuai dengan amanah. Wacana dan narasi semacam itu tampaknya merupakan usaha dari politikus yang hendak mengeksploitasi sentimen pemilih yang fanatik.
Yang juga menarik, fanatisme yang dari hari ke hari kian menguat itu akhirnya juga mendapat reaksi balik yang kurang menggembirakan dari kacamata demokrasi, yakni munculnya apatisme dari kelompok masyarakat tertentu. Beberapa kelompok di media sosial mendeklarasikan diri tak berminat terlibat dalam gegap gempita Pilpres 2019.
Survei Indikator Politik mencatat bahwa para pemilih yang tak memutuskan pilihan politiknya, yang menjadi potensi bagi terbentuknya kekuatan golput, mencapai 9,2 persen. Ada yang memprediksi bahwa kemungkinan angka golput bisa mencapai 20 persen.
Kalangan yang golput memang tak mesti dimaknai sebagai orang-orang yang apatis terhadap politik. Mereka yang sangat sadar akan politik bisa juga menjadi bagian dari kelompok golput.
Keras dan sengitnya perseteruan kubu-kubu yang bersaing, yang ditandai dengan saling serang, saling caci maki melampaui batas yang rasional bisa mengakibatkan banyak orang yang menjadi alergi, antipati lalu apatis terhadap politik. Namun, kondisi yang demikian juga bisa menjadikan seseorang yang semula memutuskan menjadi golput tiba-tiba merasa terpanggil untuk mencoblos karena menilai keadaan sudah semakin gawat dan dia merasa perlu memenangkan capres yang dinilainya cocok dengan aspirasinya.
Bagaimana mengatasi problem kedua kecenderungan ekstrem menjelang Pilpres 2019 itu? Ada dua kekuatan yang sangat dibutuhkan dalam konteks ini, yakni kaum cendekiawan dan media massa, terutama yang arus utama, baik yang elektronik maupun yang cetak.
Cendekiawan yang tidak memperlihatkan keberpihakannya terhadap kubu kontestan Pilpres 2019 perlu dijadikan narasumber utama oleh media-media massa arus utama dalam memberikan kompas kepada pemilih untuk bersikap elegan memantapkan demokrasi.
Masalahnya menjadi kian rumit ketika sebagian besar pemilik media massa arus utama adalah kalangan pemodal yang tidak bisa lepas dari kepentingan politik. Namun, keberpihakan media arus utama pada kekuatan politik tertentu tak perlu meniadakan peran mereka dalam mengatasi problem fanatisme dan apatisme pemilih.
Fungsi pendidikan, dalam konteks ini pendidikan politik menuju tahap demokrasi yang ideal substansial, perlu dijalankan media massa dengan menyuarakan opini kalangan cendekiawan yang independen yang dipercaya, baik oleh kubu petahana maupun penantang.
Tokoh-tokoh pemikir yang demikianlah yang dibutuhkan publik untuk memahami dan menyadari bahwa sikap-sikap fanatik terhadap politikus mencerminkan kenaifan dalam berpolitik. Di samping itu, publik juga perlu dipersuasi bahwa apatisme terhadap politik juga bukan sikap yang ideal karena berpolitik sejatinya berpartisipasi dalam penciptaan kesejahteraan dan keadilan.
Beberapa kali keprihatinan terhadap kaum muda yang apatis terhadap politik sempat jadi wacana publik menjelang Pilpres 2019. Para politikus pun dalam beberapa kesempatan mengajak generasi milenial untuk terjun ke dunia politik.
Seruan-seruan semacam itulah yang diperlukan untuk mengatasi kemakin menguatnya tingkat fanatisme dan apatisme menjelang ajang perebutan kekuasaan tahun ini.*
Baca juga: Kejaksaan diingatkan tak terjebak politik praktis
Baca juga: Dari debat capres, kaum milenial pelajari rekam jejak calon pemimpin
Baca juga: Prabowo rangkul oposisi bila menang Pilpres 2019
Kekhawatiran atas munculnya dua fenomena sosial itu berulang kali dilontarkan berbagai kalangan yang berkepentingan dengan berlangsungnya pemilihan presiden yang demokratis, dengan hasil yang absah sehingga diterima oleh kontestan yang berkompetisi.
Fanatisme pemilih antara lain diperlihatkan oleh semakin kerasnya perang verbal di dunia maya yang melibatkan dua pendukung fanatik masing-masing kubu, yakni kubu petahana dan kubu penantang.
Jika fanatisme itu murni bermuatan anasir politis ideologis, persoalannya relatif akan lebih mudah diurai dan ditangani. Namun, ketika fanatisme itu berkelindan dengan aspek keimanan, identitas keagamaan pemilih, problemnya semakin kusut dan semakin sulit untuk mengatasinya. Setidaknya, bukan saja pendekatan politik yang dibutuhkan tapi juga pendekatan kultural-keagamaan diperlukan untuk mengatasinya. Politikus pun perlu bantuan tokoh agama untuk menyelesaikan masalah itu.
Yang menarik dalam Pilpres 2019 adalah warna ideologis perkubuan yang terbentuk, sebagai refleksi kepentingan politik pragmatis masing-masing koalisi. Yang terjadi bukannya kontes atau rivalitas politik antara kekuatan partai politik yang nasionalis berhadapan dengan parpol yang menonjol ideologi keagamaannya.
Hal ini jelas menguntungkan dari sisi upaya meredakan intensitas persaingan sengit di antara kubu-kubu yang bersaing. Bisa dibayangkan betapa destruktif akibatnya jika parpol nasionalis seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Berkarya berhadapan dengan koalisi yang terdiri atas parpol yang secara historis beranasir keagamaan, setidaknya beridentitas keagamaan, seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.
Sekalipun koalisi yang terbentuk bersifat heterogen dalam arti campuran antara parpol yang beridentitas kebangsaan dan keberagamaan, nyatanya dalam politik riil yang terjadi tetaplah munculnya kampanye yang menggunakan simbol-simbol keagamaan, selain lambang-lambang yang berkaitan dengan sekularitas.
Dari kompleksitas yang demikianlah, publik pemilih mendapat suguhan wacana tentang dikotomi parpol setan dan parpol tuhan, yang kemudian diikuti pula narasi yang menistakan pemimpin yang kafir, dikonfrontasikan dengan pemimpin yang sesuai dengan amanah. Wacana dan narasi semacam itu tampaknya merupakan usaha dari politikus yang hendak mengeksploitasi sentimen pemilih yang fanatik.
Yang juga menarik, fanatisme yang dari hari ke hari kian menguat itu akhirnya juga mendapat reaksi balik yang kurang menggembirakan dari kacamata demokrasi, yakni munculnya apatisme dari kelompok masyarakat tertentu. Beberapa kelompok di media sosial mendeklarasikan diri tak berminat terlibat dalam gegap gempita Pilpres 2019.
Survei Indikator Politik mencatat bahwa para pemilih yang tak memutuskan pilihan politiknya, yang menjadi potensi bagi terbentuknya kekuatan golput, mencapai 9,2 persen. Ada yang memprediksi bahwa kemungkinan angka golput bisa mencapai 20 persen.
Kalangan yang golput memang tak mesti dimaknai sebagai orang-orang yang apatis terhadap politik. Mereka yang sangat sadar akan politik bisa juga menjadi bagian dari kelompok golput.
Keras dan sengitnya perseteruan kubu-kubu yang bersaing, yang ditandai dengan saling serang, saling caci maki melampaui batas yang rasional bisa mengakibatkan banyak orang yang menjadi alergi, antipati lalu apatis terhadap politik. Namun, kondisi yang demikian juga bisa menjadikan seseorang yang semula memutuskan menjadi golput tiba-tiba merasa terpanggil untuk mencoblos karena menilai keadaan sudah semakin gawat dan dia merasa perlu memenangkan capres yang dinilainya cocok dengan aspirasinya.
Bagaimana mengatasi problem kedua kecenderungan ekstrem menjelang Pilpres 2019 itu? Ada dua kekuatan yang sangat dibutuhkan dalam konteks ini, yakni kaum cendekiawan dan media massa, terutama yang arus utama, baik yang elektronik maupun yang cetak.
Cendekiawan yang tidak memperlihatkan keberpihakannya terhadap kubu kontestan Pilpres 2019 perlu dijadikan narasumber utama oleh media-media massa arus utama dalam memberikan kompas kepada pemilih untuk bersikap elegan memantapkan demokrasi.
Masalahnya menjadi kian rumit ketika sebagian besar pemilik media massa arus utama adalah kalangan pemodal yang tidak bisa lepas dari kepentingan politik. Namun, keberpihakan media arus utama pada kekuatan politik tertentu tak perlu meniadakan peran mereka dalam mengatasi problem fanatisme dan apatisme pemilih.
Fungsi pendidikan, dalam konteks ini pendidikan politik menuju tahap demokrasi yang ideal substansial, perlu dijalankan media massa dengan menyuarakan opini kalangan cendekiawan yang independen yang dipercaya, baik oleh kubu petahana maupun penantang.
Tokoh-tokoh pemikir yang demikianlah yang dibutuhkan publik untuk memahami dan menyadari bahwa sikap-sikap fanatik terhadap politikus mencerminkan kenaifan dalam berpolitik. Di samping itu, publik juga perlu dipersuasi bahwa apatisme terhadap politik juga bukan sikap yang ideal karena berpolitik sejatinya berpartisipasi dalam penciptaan kesejahteraan dan keadilan.
Beberapa kali keprihatinan terhadap kaum muda yang apatis terhadap politik sempat jadi wacana publik menjelang Pilpres 2019. Para politikus pun dalam beberapa kesempatan mengajak generasi milenial untuk terjun ke dunia politik.
Seruan-seruan semacam itulah yang diperlukan untuk mengatasi kemakin menguatnya tingkat fanatisme dan apatisme menjelang ajang perebutan kekuasaan tahun ini.*
Baca juga: Kejaksaan diingatkan tak terjebak politik praktis
Baca juga: Dari debat capres, kaum milenial pelajari rekam jejak calon pemimpin
Baca juga: Prabowo rangkul oposisi bila menang Pilpres 2019
Pewarta: Mulyo Sunyoto
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019